Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik
DOI:
https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1140Abstract
Pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Indonesia menjadi isu yang memicu kontroversi dari aspek hukum, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembangunan pagar laut dari perspektif perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip partisipasi publik diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pagar laut di wilayah pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum lingkungan serta keadilan ekologis sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut, yang sering dilakukan tanpa dokumen AMDAL dan izin pemanfaatan ruang laut yang sah, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan regulasi pesisir lainnya. Selain itu, praktik ini kerap mengabaikan partisipasi publik yang sejatinya merupakan hak konstitusional dan instrumen utama dalam menjamin keadilan ekologis. Ketimpangan akses terhadap informasi, konsultasi publik yang minim, serta kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir menjadi refleksi dari lemahnya komitmen negara terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan
References
Amaliyah. (2025). Sosiologi pendidikan: Analisis konflik pembangunan pagar laut Tangerang Selatan. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(2).
Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Arifin, S. (2012). Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jakarta: Sofmedia.
Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan tanah pantai dan wilayah pesisir di Indonesia. Perspektif Hukum, 15(1).
Baxter, B. (2005). A theory of ecological justice. New York: Routledge.
Binawan, A. A., & Sebastian, T. (2012). Menim(b)ang keadilan eko-sosial. Jakarta: Epistema Institute.
Fikarudin, W., Martadikusuma, A. D., & Pratama, S. Y. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang dari perspektif hukum progresif. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2). https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1035
Hardjasoemantri, K. (1994). Hukum tata lingkungan. Yogyakarta: UGM.
Koentjaraningrat. (1997). Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Maghribi, G., Syaputra, F. A. B., & Paat, G. R. (2025). Kajian hukum lingkungan dan implikasi sosial-ekonomi dampak pemasangan pagar laut di Tangerang. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 11(11). https://doi.org/10.3783/causa.v11i11.12520
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Prenada Media.
Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(4).
Muhdar, M. (2009). Eksistensi polluter pays principle dalam pengaturan hukum lingkungan. Mimbar Hukum, 21(1). https://doi.org/10.22146/jmh.16247
Nugraha, A. A., et al. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Jurnal Hukum Tora, 7(2). https://dx.doi.org/10.33541/jdp.v12i3.1295
Nugraha, M. R. (2025). Bolehkah HGB di atas laut? Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-hgb-di-atas-laut-lt679224be3d4d6/
Panjaitan, A. D. U., Novianti, & Farisi, M. (2021). Polluters pay principle terkait pertanggungjawaban corporate PTTEP Australasia terhadap pencemaran minyak di Laut Timur Indonesia. Uti Possidetis: Journal of International Law, 2(2).
Pramudianto, A. (2017). Hukum lingkungan internasional. Jakarta: Rajwali Press.
Purwedah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, 5(2).
Qodriyatun, S. N. (2025). Kontroversi pagar laut di Tangerang. Isu Sepekan: Bidang Ekkuibang Komisi IV DPR RI.
Saksono, H. (2013). Ekonomi biru: Solusi pembangunan berciri kepulauan studi kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Bija Praja, 5(1). https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12
Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Jakarta: Erlangga.
Sihombing, R. (2022). Cacat administrasi pembatalan sertifikat oleh BPN tanpa bantuan putusan pengadilan. Jakarta: Kencana.
Soemartono, G. P. (1996). Hukum lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Syofiarti. (2022). Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pertambangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Refleksi Hukum, 7(1). https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36
Tempo.co. (2025). Nasib warga Pulau Rempang terdampak proyek: Ada sejumlah pilihan relokasi. Tempo.co. https://www.tempo.co/politik/nasib-warga-pulau-rempang-terdampak-proyek-ada-sejumlah-pilihan-relokasi-144164
Wardana, A., & Darmawardana, D. A. (2024). Pembangunan sebagai proses eksklusi: Kajian hukum dan ekonomi-politik atas proyek strategis nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Setyo Amirullah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.






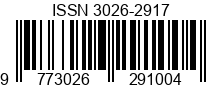
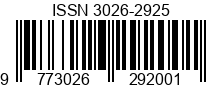




 This work is licensed under a
This work is licensed under a 